Jokowi PKI!! Ya…Jokowi PKI, tidak usah ditimbang-timbang lagi. Sekalipun fakta bahwa Jokowi lahir pada tahun 1961, dan PKI bubar sekitar 1966, artinya pada usia 5 tahun Jokowi masih sempat menjadi anggota PKI sebelum bubar. Hoax tentang Jokowi PKI terus menggema.
Beberapa tahun kemudian, La Nyala, seorang politisi terkenal, mengaku dia yang menyebarkan hoax Jokowi PKI lewat media Obor Rakyat yang kontroversial. Tapi ini tidak penting…Jokowi tetap PKI. Sudahlah, tertawakan saja.
Dunia hari ini seperti panggung besar dengan suara yang terus menggema. Media sosial berubah menjadi ruang sidang terbuka, di mana siapa pun bisa menjadi jaksa, hakim, dan eksekutor dalam satu waktu. Fenomena trial by social hoaks pun merajalela, menghancurkan reputasi dalam hitungan detik. Sebuah tuduhan dilempar, disebar, lalu dipercayai tanpa perlu pengadilan yang sah. Ironisnya, kurangnya mekanisme verifikasi hampir tak ada. Apa yang viral sering kali dianggap benar, sementara kesuliatan membadakanfakta dan opini membuat kebenaran objektif tenggelam dalam arus viralitas dan sensasionalisme serta Echo Chamber Effect.
Di tengah lautan informasi yang tidak terkendali, cancel culture dan moral policing menjadi senjata. Salah bicara sedikit? Karier dan reputasi bisa tamat. Tanpa peringatan, seseorang bisa lenyap dari panggung publik karena satu kesalahan di masa lalu. Ini bukan hanya terjadi di dunia hiburan, tetapi juga dalam dunia akademik. Tuduhan dalam dunia akademik kerap terjadi, kadang bukan soal keilmuan, melainkan karena keberpihakan politik atau kepentingan pribadi.
Ada dua hal yang selalu jadi bahan bakar hoaks: politik identitas dan polarisasi. Keduanya bekerja seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Masyarakat lebih cenderung mempercayai informasi yang mendukung kelompoknya—Confirmation Bias bermain di sini. Kalau sudah percaya, sulit untuk digoyahkan, bahkan oleh fakta. Inilah jebakan Psikologi Sosial: Konformitas dan Kebutuhan Akan Identitas, di mana perasaan lebih berkuasa daripada logika.
Ketika seseorang yang dianggap sebagai “idola” dalam kelompok melakukan kesalahan, efeknya bisa ringan karena Halo Effect—kesalahan dianggap wajar atau dimaafkan. Sebaliknya, bagi mereka yang berasal dari kelompok lawan, kesalahan sekecil apa pun bisa dibesar-besarkan karena Horn Effect. Ini menciptakan efek Echo Chamber Effect, di mana orang hanya mau mendengar apa yang ingin mereka dengar, memperkuat polarisasi.
Hoaks bukan sekadar perdebatan kebenaran. Ia bisa menjadi alat politik. Motivasi politik dan kekuasaan sering kali menjadi alasan utama kenapa sebuah berita palsu diciptakan dan disebarkan secara sistematis. Propaganda dan disinformasi digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu yang lebih besar, menciptakan distraksi dari Isu yang Lebih Besar yang membuat orang lebih sibuk berdebat soal hal-hal sepele ketimbang menyoroti kebijakan penting yang berdampak nyata.
Kemajuan teknologi tidak hanya membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Penggunaan AI dan Deepfake (gambar AI) menjadi senjata baru dalam menyebarkan disinformasi. Kini, bukan hanya teks yang bisa dimanipulasi, tetapi juga gambar dan video. Dengan teknologi ini, orang bisa dibuat terlihat mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tak pernah mereka katakan. Ini mengaburkan batas antara fakta dan fiksi, membuat publik semakin sulit membedakan mana kenyataan dan mana rekayasa.
Di era di mana hoaks menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, kurangnya literasi media dan hukum menjadi masalah serius. Banyak orang sulit membedakan antara fakta dan opini. Parahnya lagi, ada kecenderungan orang lebih suka percaya pada narasi yang menggugah emosi ketimbang yang berbasis bukti. Ini diperparah dengan Fear and Panic Response—ketika orang panik, mereka lebih mudah percaya pada informasi yang memperkuat ketakutan mereka.
Pada akhirnya, hoaks bukan hanya soal informasi yang salah. Ia juga tentang bagaimana manusia membentuk dan mempertahankan identitas kelompoknya. Identitas Kelompok dan Bias In-Group vs. Out-Group menunjukkan bahwa manusia memiliki dorongan kuat untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Keamanan dan Kelangsungan Hidup Kelompok sering kali lebih penting dibandingkan dengan mencari kebenaran objektif.
Namun, apakah loyalitas ini berbasis kebenaran atau hanya kepentingan? Di dunia politik, loyalitas berbasis keuntungan sering kali lebih dominan. Hari ini seseorang bisa mendukung seorang tokoh, besok bisa berbalik menyerangnya jika kepentingannya berubah. Menganalisis motif di balik perubahan sikap menjadi penting untuk memahami kenapa suatu narasi bisa begitu cepat bergeser.
Ketika hoaks terus diproduksi dan dikonsumsi tanpa kontrol, ketidakpercayaan pada institusi pun melemah. Orang mulai lebih percaya pada sumber informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Akibatnya, kita semakin terjebak dalam struktur sosial dan budaya yang menghidupi budaya fitnah dan gosip.
Lalu, di antara identitas dan perut, mana yang lebih dominan dalam menentukan kebenaran? Ha ha…sama saja…yang penting terus survive dan terus berada dalam grup.

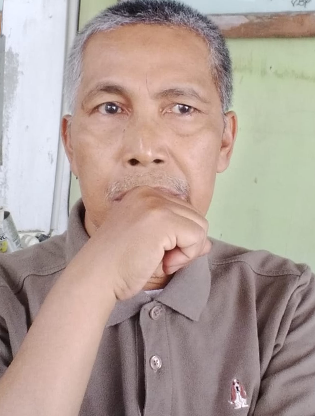
Tinggalkan Balasan