Pernahkah kamu merasa senang melihat orang lain menderita? Itu bukan pertanyaan untuk menghakimi, karena sering kali, kita tidak sadar bahwa perasaan semacam itu bisa muncul tanpa disadari. Bagi sebagian orang, kebahagiaan terletak pada melihat orang lain jatuh—entah itu fisik, emosional, atau bahkan psikologis. Entah itu karena keinginan untuk menguasai atau sekadar membuktikan bahwa kita lebih baik dari mereka. Lalu, dalam prosesnya, kebiasaan itu bertransformasi menjadi bagian dari diri kita, membentuk sikap, dan akhirnya menggerakkan tindakan.
Seorang psikolog yang kepo mempelajari dari dalam pikiran manusia bagaimana kesenangan bisa berkembang dari penderitaan. Secara tidak sadar, kita cenderung terhubung dengan rasa sakit orang lain—menganggapnya sebagai semacam penebusan untuk kekosongan yang kita rasakan. Freud pernah berbicara tentang sadisme sebagai bagian dari sisi gelap manusia yang menyukai penderitaan orang lain untuk merasakan kepuasan. Fenomena ini bisa dilihat dengan jelas pada banyak karakter dalam karya sastra terkenal.
Ambil contoh Heathcliff dalam Wuthering Heights karya Emily Brontë. Ia tumbuh dalam amarah dan kebencian, memandang dunia dengan penuh kesakitan. Semua perasaan itu kemudian membentuk kebiasaannya untuk menyakiti orang lain, terutama orang yang paling dia cintai. Dalam ketidaksadaran dan kebenciannya, Heathcliff merasa lebih kuat setiap kali orang lain menderita. Dengan mengendalikan dan merusak kehidupan orang-orang di sekitar, ia merasakan semacam pembalasan yang aneh—kebahagiaan yang dibangun dari luka yang lebih dalam. Kita bisa melihat hal ini sebagai contoh bagaimana seseorang bisa terjebak dalam siklus kesakitan dan kekuasaan yang dirasakan seolah sebagai kebahagiaan.
Namun, apakah kebahagiaan yang dibangun dengan cara ini benar-benar nyata? Bisa jadi, kebahagiaan itu hanyalah ilusi belaka, sebuah pelampiasan dari ketidakbahagiaan yang lebih mendalam. Teori behaviorisme Skinner memberikan pandangan yang menarik dalam hal ini. Dalam dunia yang penuh dengan penguatan dan hukuman, kebiasaan-kebiasaan semacam ini terbentuk dari pengalaman kita yang saling berhubungan dengan penguatan positif. Kita merasa puas ketika melihat orang lain menderita karena hal itu memberikan perasaan superioritas. Rasa senang yang datang begitu saja itu memberikan kesan bahwa kita sedang mengendalikan dunia sekitar kita, padahal itu hanya ilusi pengendalian.
Sementara itu, dalam novel The Picture of Dorian Gray karya Oscar Wilde, kita melihat Dorian Gray yang memilih untuk menghindari rasa sakit dan kenyataan dari hidupnya. Dorian mengejar keindahan dan kepuasan, mengorbankan moralitas demi kesenangan sesaat. Seiring berjalannya waktu, ia menyaksikan bagaimana gambarnya menua, sementara dirinya tetap muda dan cantik. Tindakan ini adalah cara Dorian menghindari rasa sakit yang datang dengan kehidupan dan konsekuensinya. Ia menjadi terjebak dalam kebiasaan menyakiti diri sendiri, menghindari realitas dengan cara-cara yang memanipulasi dunia di sekitarnya. Kebenaran, pada akhirnya, datang dengan cara yang brutal.
Dari sudut pandang psikologis, Dorian Gray adalah contoh seseorang yang menghindari kenyataan dan melarikan diri dari rasa sakit emosional yang mendalam. Dalam psikologi coping mechanism, sering kali kita memilih untuk melarikan diri atau menutupi rasa sakit kita dengan cara-cara yang merusak. Sama halnya dengan Dorian, yang berusaha menyembunyikan wajah tua dan penyesalannya dengan menjaga penampilan luar tetap sempurna, kita sering kali menghindar dari kenyataan pahit hidup kita. Tapi, sejauh manakah kita bisa lari dari kenyataan tanpa menghadapi konsekuensinya?
Tidak jauh berbeda dengan Raskolnikov dalam Crime and Punishment karya Fyodor Dostoevsky, yang merasa bisa mengendalikan takdirnya sendiri dengan cara yang kejam dan tidak bermoral. Raskolnikov membenarkan pembunuhannya karena ia merasa superior, lebih cerdas, dan lebih mampu daripada orang lain. Namun, saat ia menghadapi rasa bersalah dan tekanan dari tindakan yang telah dilakukannya, ia mulai merasakan penderitaan yang tak terelakkan. Penderitaan itu membawa Raskolnikov pada titik di mana ia harus menghadapi dirinya sendiri dan membuat pilihan antara terus berada dalam kebiasaan menghindari rasa sakit atau menerima dan menghadapinya.
Teori cognitive dissonance dari Leon Festinger bisa menjelaskan mengapa kita cenderung mengubah cara kita melihat dunia untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan buruk kita. Ketika kita merasa tidak nyaman dengan tindakan atau pikiran kita yang tidak konsisten, kita mencari cara untuk menyelaraskannya, meskipun itu mengarah pada tindakan yang lebih destruktif. Raskolnikov, seperti banyak dari kita, merasa perlu menemukan pembenaran untuk tindakannya, sehingga rasa sakit dan penyesalan yang sebenarnya harusnya mengarah pada perubahan justru terus mengarah pada kekosongan yang lebih besar.

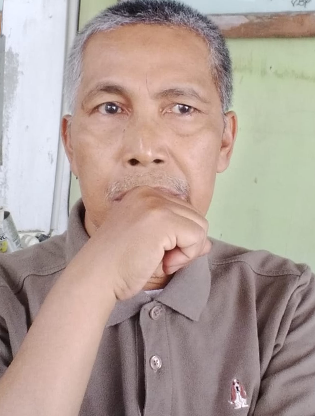
Tinggalkan Balasan